Sabtu, 10 Januari 2009
Maestro Kesenian Tradisional asal Sulsel [dua]
Cemoohan Berbuah Penghargaan
“Jika kamu tidak mau belajar menari dan menjadi penari, maka tidak ada lagi penerus yang jadi penari di keluarga kita. Kita akan kehilangan jati diri keluarga.”
*****
Pesan itu masih terngiang jelas di telinga Mak Coppong. Berkat hal itu pula, membuatnya tetap tegar menekuni “dunia” satu ini hingga di usianya yang memasuki fase uzur.
Bagi Mak Coppong, menari merupakan panggilan jiwa dan rasa. Sedangkan mengajar menari adalah tanggung jawab melestarikan budaya.
Sempat vakum lantaran dilarang, pada tahun 1977 Mak Copong bangun dari “tidur panjangnya”. Sistem pemerintahan saat itu juga telah beralih dari sistem kerajaan. Hanya saja, kali ini Mak Coppong harus berjuang sendiri.
Tapi dengan tekad bulat, diapun melangkah maju. Baginya, maju sendiri atau kolektif, sama saja. Yang penting bersungguh-sungguh, pasti akan menuai hasil maksimal.
Berbekal keyakinan itu, Mak Coppong pun mulai mengumpulkan beberapa perempuan belia untuk diajar menari. Kala itu, nyaris semua orang memandang profesi Mak Copong tidak menjanjikan dalam hal materi. Dan yang lebih menyakitkan sekaligus menjadi pelecut semangat, dia kerap dipandang sebagai wanita murahan. Dicap sebagai perempuan tidak terhormat.
“Namun saya tidak peduli dengan semua itu. Yang penting saya dipanggil untuk menghibur,
saya akan menghargai panggilan itu,” ucapnya datar.
Hasilnya, Mak Copong berhasil membuka pikiran dan hati sebagian masyarakat yang sebelumnya sering mencemoohnya. Dia bahkan berhasil memperlihatkan eksistensinya sebagai penari
primadona dan masuk dalam deretan penari berkelas tanah air.
Saat ini boleh dikata, dari enam penari tradisional Makassar, tinggal dia seorang yang tersisa
dan tetap eksis menghidupkan khazanah budaya nusantara. Lima orang sahabatnya -- satu orang telah meninggal-- memilih berhenti menjadi penari dan menekuni dunia baru.
“Katanya mereka malu. Apalagi, usianya sudah tua semua. Sama seperti saya ini,” kata Mak
Coppong mengenang rekan-rekan seprofesinya dulu.
Berkat “kepala batu” sekaligus “tebal muka”nya itu, Mak Coppong mampu mengangkat tarian
tradisional Pakarena dengan 12 jenisnya – Sambori’na, Mabbiring Kassi, Sonayya, Lambassari,
Digandang, Jangan Lea-lea, Yolle atau tari raja, Angka Malino, Lekoboddong, Anni-anni, Biseang I Lau, dan Sanro Beja-- menjadi terkenal ke seantero penjuru dunia.
Pelan tapi pasti, tarian Mak Copong mulai diapresiasi masyarakat dunia. Apalagi setelah dia
setelah bergabung di Sanggar Batara Gowa. Mak Coppong pun berubah menjadi “selebriti” tari yang pentas di mana-mana.
Ia banyak diundang ke berbagai kota, provinsi, dan negara. Puncaknya, ketika ia ikut tergabung dalam pementasan naskah I Lagaligo dari tahun 2002-2006 di Asia, Eropa, dan Amerika.
Saat tampil di Eropa dan Amerika, Mak Coppong yang tetap lugu laiknya orang kampung, sempat
menyedot perhatian penikmat tari tradisional. Maklum, dia tetap mampu mempertahankan “keasliannya“ sebagai penari tradisional; sederhana namun bersahaja.
Seiring dengan itu, sederet penghargaan pun berhasil diraiahnya. Antara lain Anugerah Seni
dari Dinas Pariwisata Sulsel (2000), Penghargaan dari Menteri Pariwisata Seni dan Budaya RI (1999), serta yang terkini, dinobatkan sebagai maestro tari tradisi asal Sulsel.
Meski mendapat predikat itu, Mak Coppong tak pernah merasa puas. Di usianya yang kian
uzur, nenek dari delapan cucu ini masih terus menari. Untuk mempertahankan tradisi itu, ia mengajak seluruh keluarga, anak, kemenakan, dan cucu-cucunya untuk menari.
Meski diakui tidak ada perhatian dari pemerintah Kabupaten Gowa terhadap dirinya, namun
hal itu tidak menjadi penghambat. Sebab dalam hati Mak Coppong tertanam satu tekad dan keyakinan bahwa “kekayaan” yang dimilikinya sekarang tak bisa dinilai dengan benda apapun. (bersambung)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


















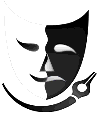


Tidak ada komentar:
Posting Komentar